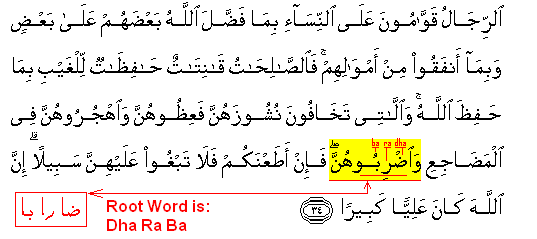Oleh Sandy Arifiadie Pendahuluan
Banyak dari kalangan muslim maupun nonmuslim yang sering bertanya-tanya mengenai pernyataan Alquran yang mengatakan secara harfiah kepada kaum laki-laki untuk “memukul mereka”, yang berarti istri mereka, dalam Surat Annisa 4:34. Ayat ini begitu kontroversial sehingga sering dipakai para orientalis untuk menuding bahwa Islam adalah agama yang tidak toleran dan merendahkan martabat kaum perempuan.
Beberapa ahli hukum menentang bahwa bahkan walaupun “pemukulan terhadap istri” diperbolehkan dengan “legitimasi Alquran”, hal itu tetaplah menakutkan. Film berjudul Submission, yang terkenal setelah pembunuhan sutradaranya Theo van Gogh, berusaha mengupas ayat Alquran ini dan sejenisnya dengan memperlihatkan gambaran yang melukiskan tubuh-tubuh perempuan muslim yang teraniaya. Ayaan Hirsi Ali, penulis film, mengatakan “Tertulis dalam Alquran bahwa seorang perempuan boleh ditampar jika dia tidak menuruti keinginan mereka. Ini merupakan salah satu dari tindak kejahatan yang saya harap bisa menunjukkannya dalam film ini.”
Diakui oleh para ulama, ayat Annisa 4:34 ini memang sering dipakai kaum laki-laki (muslim) yang tidak mengerti Alquran sebagai legitimasi untuk melakukan perbuatan kejam dan diskriminasi terhadap istri mereka yang tidak mau mematuhi kehendak mereka. Kaum perempuan disuruh untuk tunduk sepenuhnya kepada perintah suaminya, seperti tunduk kepada Allah, tak peduli perintahnya itu baik atau tidak menurut Allah. Benarkah demikian?
Terjemahan Ayat
Mengenai Annisa 4:34 yang sering disalahpahami ini, pertama-tama, mari kita tengok langsung ke dalam naskah asli Alquran (berbahasa Arab), yang diikuti dengan bunyi fonetis dalam huruf Latin, setelah itu barulah diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia beserta penjelasannya.
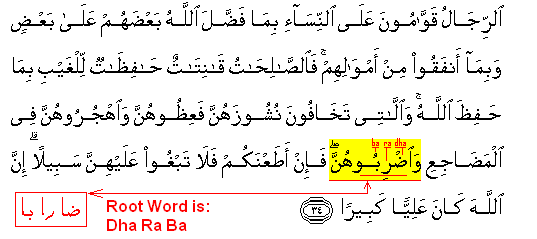
Arrijaalu qawwamuuna ‘alaa annisa-i bima faddhala Allahu ba’dhahum ‘alaa ba’dhin wa bimaa anfaqu min amwalihim; fasshalihatu qaanitaatun hafizhaatul lilghaibi bimaa hafizha Allahu, wallatii takhafuuna nusyuuzahunna fa’izhuhunna wahjuruuhunna fii almadhaji’i wadribuuhunna fa-in ata’nakum falaa tabghuu ‘alaihinna sabiilan; inna Allaha kaana ‘aliyyan kabiiran.
Berikut adalah terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan tafsiran ayatnya sesuai dengan ajaran Muhammad dalam Kitab Hadis seperti yang dijelaskan oleh para ahli:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Annisa 4:34, Departemen Agama)
Kaum laki-laki itu adalah kepala bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan, dan karena laki-laki telah [diwajibkan untuk] menafkahkan sebagian dari harta mereka [untuk kebutuhan perempuan]. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya, [yang baik dan menjaga diri dari dosa itu,] tidak ada, dan [memelihara] apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka [kesucian dirinya, harta bersama, kehormatan suami, dan lainnya]. Mengenai perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan pembangkangannya [dengan melakukan perbuatan tidak senonoh, berzinah, tak menjaga diri, berbuat sesuatu yang dilarang Allah], maka nasihatilah mereka; atau [jika masih berbuat seperti itu,] pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka; atau [jika masih berbuat seperti itu,] pukullah mereka [tetapi jangan sampai menyakiti dan melukai mereka]. Kemudian jika mereka menaatimu [untuk kembali berkelakuan sopan dan mengikuti perintah Allah untuk menjauhkan diri dari dosa tersebut], maka janganlah kamu mencari-cari cara untuk menyusahkannya; [hai kaum laki-laki yang telah mendapat hikmat dan pengertian yang benar tentang hukum Allah.] Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An-Nisa 4:34, terjemahan bebas)
Men are the maintainers of women because God has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as God has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely God is High, Great. (Annisa 3:34, Ash-Shakir)
Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend (to support them) from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient (to Allâh and to their husbands), and guard in the husband's absence what Allah orders them to guard (e.g. their chastity, their husband's property, etc.). As to those women on whose part you see illconduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly, if it is useful), but if they return to obedience, seek not against them means (of annoyance). Surely, Allah is Ever Most High, Most Great. (Annisa 3:34)
Penjelasan Ayat dan Kesalahan Penafsiran
Para sarjanawan Islam (ulama) dan apolog Islam lain memiliki respons yang berbeda atas kritik-kritik para orientalis mengenai Annisa 3:34 ini.
Alquran memang mengizinkan suami—tentu saja yang telah berserah diri sepenuhnya kepada Allah—untuk menghukum istrinya karena terbukti dengan jelas (bukan sekedar asumsi) melewati batas-batas yang diberikan Allah, yaitu melakukan apa yang dilarang Allah. Meskipun demikian, Alquran dan Muhammad lewat Hadis tetap memberi wejangan bahwa seorang laki-laki, jika ia mau, hanya diperbolehkan untuk “memukul” istrinya dengan sangat perlahan sehingga tidak meninggalkan bekas di tubuhnya, kecuali laki-laki itu sendiri juga telah melewati batas-batas hukum Allah (sama-sama memelihara dosa). Hal ini dimaksudkan hanya sekedar untuk menyadarkan istri, dan bukan untuk melampiaskan rasa kesal dan dendam suami.
Begitu pula menurut kebanyakan sarjanawan Islam dan para penafsir. Mereka telah menekankan bahwa “pemukulan” itu, ketika diperbolehkan, bukanlah untuk dilakukan dengan kasar atau bahkan mereka haruslah ditafsirkan kurang lebih secara simbolis. Menurut Abdullah Yusuf Ali dan Ibn Katsir, para ulama muslim bermufakat bahwa ayat di atas menggambarkan pemukulan yang ringan. Banyak sarjanawan muslim menjelaskan bahwa pemukulan tersebut hanya tepat jika seorang perempuan telah melakukan “pekerjaan yang keji, berdosa, nakal, dan memberontak” di luar ketidakpatuhan biasa terhadap keinginan suami.
Akar kata dharaba yang dalam ayat di atas menjadi udhribu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “memukul” dan ke dalam bahasa Inggris sebagai “beat” (memukuli dengan keras). Kata udhribu tersebut secara literal berarti to strike (memukul). Terdapat banyak penerjemahan literal, pada berbagai versi terjemahan, dalam menggunakan kosakata ini, mulai dari “tepuklah”, “berjalanlah dengan tenang”, “lecutlah secara ringan”, “pukullah (sesuatu)”, “berikan contoh yang jelas”, hingga “pukullah”.
Sedangkan, dalam terjemahan bahasa Inggris dari Mohammed Habib Shakir di atas, kosakata dalam bahasa Inggris “beat” untuk kata tersebut adalah terjemahan yang tidak tepat. Begitu pula dalam terjemahan bahasa Inggris pada masa lalu, selain menggunakan kata “beat” (memukul keras) atau “hit” (menampar), ada pula yang menerjemahkannya sebagai “scourge” (mencambuk). Kata-kata yang dipakai tersebut menampilkan kesan yang tidak benar akan suatu pemukulan keras yang diizinkan. Sebaliknya ia diterjemahkan menjadi “strike”, ini akan meliputi keseluruhan rentang mulai dari tepukan halus hingga tonjokkan penuh tenaga.
Ada pula pendapat lain seperti Raghib yang menyampaikan bahwa dharaba secara metaforis berarti “berhubungan seksual”, dan mengutip ungkapan “darab al-fahl an-naqah” (unta bertiang menutupi unta betina), yang juga dikutip dalam Lisan al-‘Arab. Dalam ungkapan ini jelas kosakata tersebut tidak diartikan sebagai 'memukul mereka (perempuan).' Pandangan ini diperkuat dengan hadis sahih Muhammad yang ditemukan dalam sejumlah riwayat, termasuk Bukhari dan Muslim: “Dapatkan salah satu dari kalian memukul istrinya padahal kalian seorang hamba, lalu tidur dengannya pada malam harinya?” Ada juga riwayat lain dari Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya, yang menyatakan bahwa Muhammad melarang pemukulan terhadap perempuan, dan berkata: “Jangan pernah memukul dayang-dayang Allah!” (Sumber: Alquran: sebuah terjemahan kontemporer oleh Ahmed Ali, Princeton University Press, 1988; hlm. 78-79)
Ia menerjemahkan tiga kata seperti fa'izu, wahjaru, dan wadhribu dalam teks asli masing-masing sebagai ‘berbicara kepada mereka dengan sikap persuasif’, ‘meninggalkan mereka sendiri (di tempat tidur, fil madhaji'i)’, dan ‘berhubungan seksual’ (lihat Raghib Lisan al-'Arab dan Zamakhsari). Raghib dalam kitab Al-Mufridat fi Gharib Alquran memberikan makna dari kata-kata tadi dengan referensi khusus yang relevan. Fa-'izu, menurutnya, berarti 'berbicara kepada mereka secara persuasif untuk meluluhkan hati mereka.' (Lihat juga Annisa 4:63, di mana kata tersebut dipakai untuk pengertian yang sama.) Hajara - Wahjaru, menurutnya, berarti memisahkan tubuh dari tubuh, dan menyampaikan bahwa ekspresi wahjaru-hunna secara metaforis berarti menahan diri untuk tidak menyentuh dan menganiaya mereka. Zamakhshari secara eksplisit dalam Kashshaf menjelaskan, 'jangan masuk ke dalam selimut mereka.'
Berikut adalah terjemahan ayat tersebut, dengan memasukkan kata dharaba menurut penafsiran mereka, sejauh yang bisa didefinisikan menurut aturan penerjemahan sesuai penjelasan para ahli tersebut:
“Kaum laki-laki itu adalah kepala bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita, dan karena laki-laki telah diwajibkan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya (yang saleh dan takut kepada Allah itu,) sedang tidak ada, dan memelihara apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka (yaitu, kesucian dirinya, harta bersama, kehormatan suami, dan lainnya). Mengenai perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan pembangkangannya (dengan melakukan perbuatan tidak senonoh, berzinah, tak menjaga diri, berbuat sesuatu yang dilarang Allah), maka nasihatilah mereka; atau (jika masih berbuat seperti itu,) pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka; atau (jika masih berbuat seperti itu,) [berikan dia pengertian yang sangat tegas dan pilihan antara meluruskan sifatnya tersebut atau bercerai, dan apabila perempuan itu kembali berkelakuan sesuai hukum Allah, kembalilah berbagi tempat tidur bersamanya]. Kemudian jika mereka menaatimu (untuk kembali berkelakuan sopan dan mengikuti hukum Allah), maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya; (hai kaum laki-laki yang telah mendapat hikmat dan pengertian yang benar tentang hukum Allah.) Sesungguhnya ALLAH Mahatinggi lagi Mahabesar.”
Menurut penjelasan mereka, bagian pertama ayat 34 berhubungan dengan hal kaum laki-laki yang diwajibkan melindungi kaum perempuan. Selanjutnya menjelaskan bahwa seorang istri harus taat kepada Allah karena Dialah yang telah menyediakan kebutuhan hidup dan perlindungan baginya dan harus mengargai dan menghormati suaminya, menjaga dirinya sendiri dan harta milik suaminya saat suaminya tidak ada. Seorang laki-laki diberitahukan cara yang pantas untuk berperilaku ketika ia mendapati istrinya tidak bertingkah laku pantas dan sopan sebagai seorang perempuan baik-baik. Seorang suami yang baik mendapat perintah langsung untuk mulai mengingatkan istrinya yang berkelakuan tidak baik itu dengan sopan dan tanpa menyakiti hati, dan jika dia rela untuk meninggalkan perbuatannya, jangan beri dia kesulitan lagi. Namun, jika kelakuan buruknya berlanjut, suami tidak boleh bercampur dengannya; dan ini akan membuat semua jelas baginya bahwa maksud suami sangat serius dan itu bukanlah lelucon. Selain itu, jika si istri telah mengerti dan sadar akan kesalahannya lalu suami harus membiarkannya dan jangan mengganggunya lagi dengan mengulas-ulas hal tersebut. Terakhir, jika istri masih bersikeras melakukan perbuatan kotornya, laki-laki harus berkata tegas kepadanya tanpa ragu-ragu bahwa mereka harus berpisah atau bahkan mengakhiri pernikahan mereka kecuali sang istri kembali berkelakuan dengan pantas. Sedangkan, jika perempuan mau patuh, maka suami tidak boleh melanjutkan permasalahan ini dan harus kembali berbagi tempat tidur dengannya.
Bagaimanapun juga, perlu dijelaskan bahwa bahasa Indonesia, salah satu bahasa ‘ajjam atau non-Arab, merupakan bahasa yang tidak baik untuk menerjemahkan, kata per kata, maksud dari bahasa Arab Alquran. Begitu pula bahasa lainnya di dunia, terutama non-Semitik. Oleh karena itu, yang kita punya adalah terjemahan kata berdasarkan pengertian terbaik yang dimiliki sang penerjemah—disesuaikan dengan kosakata yang cocok atau mendekati.
Dan tentu saja ini semua merupakan suatu usaha untuk menafsirkan satu frasa pendek namun sangat kuat maknanya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sumber dikutip di sini dan mungkin masih banyak interpretasi lain namun yang bisa diterima hanyalah yang berlandaskan ajaran Alquran dan ajaran Muhammad, yang tertulis dalam Hadis, secara menyeluruh—bukan setengah-setengah. (Sumber: Alquran: sebuah terjemahan kontemporer oleh Ahmed Ali, Princeton University Press, 1988; hlm. 78-79)
Pengertiannya sekarang adalah bahwa beberapa penerjemah tidak menggambarkan nuansa maknanya dengan baik. Bagaimanapun setiap bahasa memiliki kekayaan kosakata yang berbeda, dan bahasa Arab memiliki kekayaan kosakata dan makna yang berbeda dari bahasa-bahasa lainnya. Karena itu, terjemahkan-terjemahan itu tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai representasi dari apa yang dimaksudkan oleh Allah yang Mahakuasa.
Kata Dharaba dalam Ayat Lain
Satu-satunya arti yang bisa dilakukan terhadap apa yang ada dalam Kitab Suci haruslah menggunakan aturan-aturan dalam Kitab Suci, yaitu Alquran. Dan Allah telah menggunakan kosakata yang sama beberapa kali secara konsisten dengan maksud yang sama. Mari kita periksa bersama.
Selain itu, salah satu aturan untuk mengerti kata-kata dalam Alquran dalah pergi ke bagian-bagian lain dalam Alquran untuk memeriksa pemakaian kata yang sama di bagian lain; dan kata ini digunakan oleh Allah dalam bagian lain dalam Alquran untuk menunjukkan “membuat” atau “merancang untukmu” atau “membertahu kepadamu” Kata ini digunakan oleh Allah dalam beberapa tempat lain dalam Alquran untuk mengartikan “membuat” atau “membuat sebuah penyataan jelas untukmu” atau “membuatnya diketahui olehmu”—seperti yang dicontohkan dalam ayat-ayat berikut:
Ar-Raad 13:17, “…kadzaalika yadhribu Allahul amtsal…” (…demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan (amsal-amsal)…)
[di sini kata “yadhirbu” berasal dari akar kata yang sama, dha-ra-ba]
Ibrahim 14:24, “Alam tara kaifa dharaba Allahu matsalan...” (Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan...)
Dan, lagi, dalam ayat berikutnya:
Ibrahim 14:25b, “…wa yadhribu Allahul amtsala linnaasi.” (Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia …)
[lagi, kata yadhirbu berasal dari dha-ra-ba]
Annur 24:35, “…wa yadhribu Allahu aamtsala linnaasi…” (…dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia…)
Arrum 30:28, “Dharaba lakum matsalan min anfusikum…” (Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri…)
Attahrim 66:10, “Dharaba Allahu matsalan lilladziina kafaruu..” (Allah membuat (bagi istri Nuh dan istri Lut) perumpamaan bagi orang-orang kafir…)
Sebagian ayat lain yang memakai kata dharaba di bawah ini diterjemahkan sebagai “memukul” adalah:
Al-araf 6:160, “Anidhrib bi’ashaakal hajar…” (Pukullah batu itu dengan tongkatmu!)
Alanfal 8:50, “Walautaraa idz yatawaffal ladzii kafaruul malaaikatu wadhribuuna wujuuhahum wa adbaarahum…” (Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka.)
Annuur 24:31, “…wa laa yadhribna biarjulihinna liyu’lama maa yukhfiina min ziinatihinna…” (Dan janganlah mereka memukulkan (menghentakkan) kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.)
Assyuura 26:63, “Anidhrib bi’ashaakal bahr…” (Pukullah lautan itu dengan tongkatmu.)
Ashshafat 37:93, “…faraagha ‘alaikum dharban bilyamiin…” (Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).)
Shad 38:44, “Wakhudzbiyadika dhightsan faadhrib bihi…” (Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu.)
Faktanya, kata dharaba di atas tidak hanya diterjemahkan sebagai “memukul” atau “menampar” pada ayat-ayat di atas. Dan berikut adalah ayat-ayat yang memakai kata selain “dharaba” untuk diterjamahkan sebagai “memukul”:
Albaqarah 2:275, “...kama yaqaamu allati yatakhabbatuhu ash-shaytanu mina almassi…” (…seperti berdirinya orang yang kemasukan (dipukul mundur) setan lantaran (tekanan) penyakit gila...);
Almaidah 5:3, “Hurrimat ‘alaikumul maitatu wad damu walahmul khinziiri wa maa uHilla li-ghairillaahi bihii wal munkhaniqatu wal mauquudzatu wal mutaraddiyatu wan nathiihatu wa maa akalas sabu’u…” (Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih dalam nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas…);
Al-anaam 6:93, “…wal malaaikatu baashithu aidihim…” (sedang para malaikat memukul dengan tangannya…);
Dan dalam Taha 20:18, Allah berkata, “Qaala hiya Aasaya atawakkau ‘alaiha waahushshu biha ‘ala ghanamii waliya fiiha maaribu ukhra.” (Ini adalah tongkatku, aku bersandar padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya.).
Seperti yang kita lihat, ketiga kata yang dipakai bahkan tidak ada hubungannya dengan kata dharaba.
Apa yang Dikatakan Sang Nabi?
Jika hanya membaca dan menafsirkan dari Alquran saja, baik muslim maupun nonmuslim, akan kesulitan mendapatkan pengertian yang benar dan menyeluruh mengenai maksud suatu ayat—malah hanya akan timbul kesalahpahaman dan penolakan, seperti pada Annisa 3:34 ini. Hanya dengan beralih pada sabda Muhammadlah maka pengertian yang benar mengenai Alquran di atas diperoleh. Terdapat banyak sabda Nabi yang relevan guna memahami secara benar ayat Alquran di atas. Merangkum hadis-hadis ini dengan segera dapat ditemukan bahwa suami bahkan tidak diperbolehkan untuk “memukul” istri-istri mereka, kecuali dalam kasus “perilaku yang berat/ menghebohkan,” dan bahkan mereka tidak boleh “menjatuhkan pada mereka hukuman berat apapun” Lebih dari itu, seorang suami diperintahkan bahwa ia tidak boleh “memukul di wajah (istri)-nya” dan sebagainya
‘Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami meriwayatkan bahwa ia mendengar Nabi berkata dalam khotbah perpisahannya di akhir Haji Terakhirnya, setelah beliau memuliakan dan memuja Allah, ia memperingatkan para pengikutnya: “Dengarkan! Perlakukan perempuan dengan baik … Andai mereka bersalah karena perbuatan yang keji, engkau boleh memindahan mereka dari ranjangmu, dan memukul ringan mereka, tetapi jangan kenakan pada mereka hukuman keras apapun …” (Tirmizi 276)
Hakim bin Muawiyah al Qusyairi mengutip ayahnya berkata bahwa ia bertanya pada Rasul Allah: “Apakah hak seorang istri kami terhadap suaminya?” Rasul Allah menjawab: “Bahwa engkau harus memberinya makanan ketika engkau makan, memberinya pekaian ketika engkau memakaikan baju pada dirimu, tidak memukulnya di wajahnya, tidak mengehinakan atau memisahkan dirimu dari dirinya kecuali di dalam rumah.” (Abu Daud 2137)
Abdullah bin Zama meriwayatkan bahwa Nabi melarang menertawakan seseorang yang bersendawa dan berkata, “Bagaimana mungkin salah satu di antara kalian memukuli istrinya seperti ia memukuli unta, lalu tidur dengannya?” (Bukhari 8:68)
Utusan Allah … menyapa orang-orang, dan berkata … “Takutlah pada Allah berkenaan dengan perempuan! Sesungguhnya engkau telah mengambil mereka pada perlindungan Allah, dan mencampuri mereka telah halal bagimu melalui kata-kata Allah. Engkau juga memiliki hak atas mereka, dan bahwa engkau semestinya tidak memperbolehkan siapapun yang tidak engkau sukai duduk di ranjangmu (sama seperti engkau yang juga tidak boleh melakukannya dengan perempuan lain yang tidak halal). Tetapi jika melakukannya, engkau boleh menghukum mereka, tetapi jangan berat-berat …” (Muslim 2803)
Terdapat jaminan terhadap status istri dalam sebuah pernikahan antara seorang muslim, dengan catatan bahwa yang terbaik di antara mereka adalah “mereka yang bersikap baik terhadap istri-istri mereka”:
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul Allah berkata: “Muslim yang paling sempurna dalam keimanan adalah ia yang memiliki perilaku yang sangat terpuji (dan membawa damai), yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang berperilaku paling baik terhadap istri-istrinya (dan membawa damai bagi mereka).” (Tirmizi 278; lihat juga 628 dan 3264)
Keseluruhan periwayatan hadis di atas mengilustrasikan bahwa Annisa 4:34 tidak memperbolehkan seorang suami “memukul” istrinya dengan cara apapun yang dapat menyebabkan cedera atau luka fisik.
Kesimpulan
Sekarang kita dapat memahami dengan baik bahwa Allah Yang Mahakuasa telah memerintahkan laki-laki muslim yang sejati untuk menafkahi perempuan dan mengizinkan mereka untuk menyimpan semua kekayaan, warisan, dan pendapatan mereka tanpa menuntut apapun dari mereka sebagai dukungan dan pemeliharaan.
Ayat 34 dan 35 dalam Surat Annisa perlu dibaca bersamaan untuk mengerti bahwa konteksnya menggambarkan hubungan yang semestinya antara laki-laki dan perempuan secara umum, dan antara suami dan istri secara khusus. Islam mencarikan jalan untuk menjaga keutuhan keluarga, dan untuk membawa damai, dan untuk rekonsiliasi antara pasangan. Ayat berikutnya membuat semakin jelas apa yang harus dilakukan ketika nampak bahwa perceraian mungkin akan terjadi sebagai akibat dari kelakuan buruk yang tidak diperbaiki. Ayat tersebut juga menekankan pada juru pisah yang ditunjuk dari kedua pihak dan mencari rekonsiliasi.
Bagaimanapun juga, hubungan suami dan istri dalam suatu pernikahan itu laksana busana satu sama lain, masing-masing menawarkan perlindungan dan kehangatan. Lebih dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang lebih dekat kecuali pakaiannya sendiri.
…Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka (Albaqarah 2:187b)
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Arrum 30:21)
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Annisa 4:19, Departemen Agama)
Maka, jika perempuan sudah pasti bersalah karena melakukan perbuatan kotor dan tidak senonoh, maka seorang suami harus bisa berbicara lebih dulu dengannya dengan sopan dan penuh pengertian, menasihati atau mengingatkannya, sehingga seorang istri bisa berhenti melakukan perbuatan keji itu—sekedar catatan, seorang suami tidak boleh sampai ikut melakukan perbuatan dosa. Namun, jika seorang istri ternyata melanjutkan perbuatan tidak senonoh itu, maka suami diperbolehkan untuk tidak lagi berbagi tempat tidur dengannya, dan hal ini akan berlangsung selama beberapa waktu. Terakhir, jika istri lantas menyesali perbuatannya dan bertobat, maka seorang suami wajib menerima dia kembali dan berbagi tempat tidur lagi dengannya. Hanya sebagai alternatif paling akhirlah seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya yang berbuat tidak baik itu dan itu tergantung pada kesabaran dan kecerdasan suami dalam menghadapinya.
Ringkasnya, “pemukulan” yang merujuk dalam Annisa 4:34 lebih mendekati suatu psikodrama pribadi di mana suami secara simbolis mengekspresikan ketidaksukaannya untuk membuat sang istri sadar akan perbuatan buruknya. Ini serupa dengan idiom orang Amerika “to strike/ to hit with a wet noodle” (“memukul dengan bakmi basah”). Persis seperti pedagang Venesia Shakespeare, yang hanya bisa memperoleh satu pon daging, hanya jika ia tidak mengucurkan setetes darah pun; maka seorang suami dapat “memukul” istrinya hanya jika ia tidak menyebabkan penderitaan fisik, cedera, atau luka.
Sumber:
· www.islamtomorrow.com
· www.searchtruth.com
· Dirks, Jerald F.: The Abrahamic Faiths: Judaism, Christianity, and Islam Similarities and Contrasts. Betsville, Amana Publications, 2004.
· Departeman Agama Republik Indonesia: Al-Qur’an dan Terjemahannya. Semarang, CV. Adi Grafika Semarang, 1994.
(www.sammy-summer.co.cc)